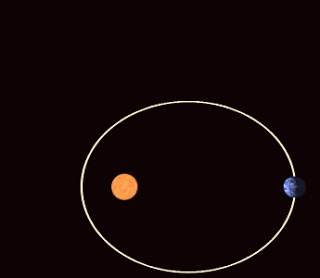Einstein, Agama, Muthahhari
Oleh: Sulaiman Djaya, penyair di Kubah Budaya
Paska abad pertengahan di Eropa, agama di benua itu dituding sebagai penyebar takhayul dan kemunduran (kejumudan) bangsa-bangsa Eropa. Itulah masa-masa renaisans dan sekulerisme Eropa menjadi gerakan politik, kebudayaan dan intelektual yang akan menggusur dominasi politik dan budaya gereja yang telah membentuk alam-pikiran dan praktik sosial-politik-budaya selama berabad-abad sebelumnya. Namun, sebagai isu metafisik dan santifik, persoalan agama dan terutama eksistensi Tuhan, tak pernah bisa berakhir.
Di tahun 1927, para ahli fisika berkumpul di sebuah ruangan yang berada dalam sebuah gedung besar. Pagi itu, di luar gedung, salju turun ragu-ragu, saat itu awal musim dingin mulai datang, pelan dan lamban, namun pasti membuat beku segala yang disentuhnya. Kebanyakan orang memilih berlindung di balik selimut, cuaca awal musim selalu disambut dengan kemalasan. Tapi tidak dengan para ahli fisika di ruang gedung itu. Mereka berdebat, dan sepertinya tidak menemukan konklusi ajeg bersama.
Mereka adalah Max Planck, Pauli, dan Heisenberg, yang sedang membahas tentang Albert Einstein, teoritikus fisika terbesar masa itu, bahkan hingga saat ini. Diskusi mereka menitik pada pokok soal, Einstein yang terlalu sering berbicara tentang Tuhan dalam setiap esai dan ceramahnya, seperti ketika Einstein menulis, “aku ingin membaca pikiran Tuhan”, “Tuhan tidak bermain dadu”, dan yang lainnya.
Lalu bagaimana para ilmuwan itu harus menyikapi kelakuan Einstein tersebut? Setelah perdebatan sengit, akhirnya Pauli menyatakan: “Kalau batas antar bidang-bidang pemikiran dan pengalaman kita semakin menajam, pada akhirnya kita akan masuk pada sebuah kesepian yang menakutkan dan kita harus ijinkan air mata menetes di pipi kita”.
Itulah sebabnya, sebagai ilmuwan (fisikawan), Einstein menolak konsepsi Tuhan yang antroposentris (Tuhan yang dibayangkan seumpama manusia). Einstein melihat ide Tuhan personal sebagai bentuk antropomorfisme (seperti contohnya doktrin Mujassimah Wahabi yang menganggap Tuhan punya tangan dan bertempat).
Pada intinya, seperti alam, Tuhan adalah misteri tak terlukiskan dengan bahasa manusia. Mengapa demikian? Karena ia pun tidak bisa melukiskan batas sepi kosmos, sehingga ia pun harus terpaksa berhenti pada E=MC2. Itupun tidak juga menuntaskan misteri kosmos. Kosmos dan Tuhan tetap misteri yang tak akan pernah terungkap tuntas.
Dalam hal ini, Imam Ali bin Abi Thalib as pernah berkhutbah: “Ia yang untuk menggambarkan-Nya tak ada batas telah diletakkan, tak ada pujian yang maujud, tak ada waktu ditetapkan, dan tak ada jangka waktu ditentukan. Ia mengadakan ciptaan dengan kodrat-Nya, menebarkan angin dengan rahmat-Nya, dan mengukuhkan bumi yang goyah dengan batu”.
Khutbah Imam Ali bin Abi Thalib as itu telah menjawab kebuntuan yang dialami para ilmuwan, terutama para fisikawan, baik di era keemasan Islam masa Dinasti Abbasiyah hingga era mutakhir kita saat ini. Sampai saat ini pun, para ilmuwan (termasuk para fisikawan tentu saja) bahkan belum sanggup menjawab mula semesta serta keluasan dan batasnya.
Sebenarnya, menurut Ayatullah Murtadha Muthahhari, perlawanan Eropa terhadap gereja dan kekristenan karena memang secara inheren doktrin gereja bertentangan dengan akal dan rasionalitas. Tidak demikian dengan Islam: “Ilmu pengetahuan memberikan kepada kita cahaya dan kekuatan. Agama memberi kita cinta, harapan dan kehangatan. Ilmu pe¬ngetahuan membantu menciptakan peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Agama menetapkan maksud upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Ilmu pengetahuan membawa revolusi lahiriah (material). Agama membawa revolusi batiniah (spiritual). Ilmu pengetahuan menjadikan dunia ini dunia manusia. Agama menjadikan kehidupan sebagai kehidupan manusia”.
Ayatollah Murtadha Muthahhari, ketika melihat hubungan, interaksi, atau dialektika antara agama (Islam) dan sains ini, memang memandang agama dengan paradigma harmonis dan saling melengkapi, bukan saling bertentangan sebagaimana Eropa ketika memberontak dan melawan dogma dan dominasi gereja paska abad pertengahan itu: “Hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama dapat dibahas dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah kita lihat apakah ada sebuah agama yang konsepsinya melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan yang ilmiah itu bertentangan dengan agama, tidak memberikan harapan dan tidak melahirkan optimisme.
Sudut pandang kedua yang menjadi landasan dalam membahas hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan adalah pertanyaan tentang bagaimana keduanya ini berpengaruh pada manusia. Apakah ilmu pengetahuan membawa kita ke satu hal, dan agama membawa kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan satu hal itu? Apakah ilmu pengetahuan mau membentuk (karakter) kita dengan satu cara dan agama dengan cara lain? Atau apakah agama dan ilmu pengetahuan saling mengisi, ikut berperan dalam menciptakan keharmonisan kita semua? Baiklah, kita lihat sumbangan ilmu pengetahuan untuk kita dan sumbangan agama untuk kita.
Ilmu pengetahuan dan agama sama-sama memberikan kekuatan kepada manusia. Namun, kekuatan yang diberikan oleh agama adalah berkesinambungan, sedangkan kekuatan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan terputus-putus. Ilmu pengetahuan itu indah, begitu pula agama. Ilmu pengetahuan memperindah akal dan pikiran. Agama memperindah jiwa dan perasaan. Ilmu pengetahuan dan agama sama-sama membuat manusia merasa nyaman. Ilmu pengetahuan melindungi manusia terhadap penyakit, banjir, gempa bumi dan badai. Agama melindungi manusia terhadap keresahan, kesepian, rasa tidak aman dan pikiran picik. Ilmu pengetahuan mengharmoniskan dunia dengan manusia, agama menyelaraskan manusia dengan dirinya.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa akibat dari memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, telah terjadi kerugian yang tak dapat ditutup. Agama harus dipahami dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, sehingga tidak terjadi pembauran agama dengan mitos. Agama tanpa ilmu pengetahuan berakhir dengan kemandekan dan prasangka buta, dan tak dapat mencapai tujuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, agama menjadi alat bagi orang-orang pandai yang munafik. Kasus kaum Khawarij pada zamah awal Islam dapat kita lihat sebagai satu contoh kemungkinan ini. Contoh lainnya yang beragam bentuknya telah kita lihat, yaitu pada periode-periode selanjutnya, dan masih kita saksikan.
Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah seperti sebilah pedang tajam di tangan pemabuk yang kejam. Juga ibarat lampu di tangan pencuri, yang digunakan untuk membantu si pencuri mencuri barang yang berharga di tengah malam. Itulah sebabnya sama sekali tak ada bedanya antara watak dan perilaku orang tak beriman dewasa ini yang berilmu pengetahuan dan orang tak beriman pada masa dahulu yang tidak berilmu pengetahuan. Lantas, apa bedanya antara Churchill, Johnson, Nixon dan Stalin dewasa ini dengan Fir’aun, Jenghis Khan dan Attila pada zaman dahulu?
Dapatlah dikatakan bahwa karena ilmu pengetahuan adalah cahaya dan juga kekuatan, maka penerapannya pada dunia mate¬rial ini tidaklah khusus. Ilmu pengetahuan mencerahkan dunia spiritual kita juga, dan konsekuensinya memberikan kekuatan bagi kita untuk mengubah dunia spiritual kita. Karena itu, ilmu pengetahuan dapat membentuk dunia dan manusia juga. Ilmu pengetahuan dapat menunaikan tugasnya sendiri, yaitu mem¬bentuk dunia dan juga tugas agama, yaitu membentuk manusia. Jawabannya adalah bahwa semua ini memang benar, namun masalah pokoknya adalah bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang penggunaannya tergantung kepada kehendak manusia. Apa saja yang dilakukan oleh manusia, dengan bantuan ilmu pengetahuan dia dapat melakukannya dengan lebih baik. Itulah sebabnya kami katakan bahwa ilmu pengetahuan membantu kita mencapai tujuan dan melintasi jalan yang kita pilih”.
Dan akhirnya memang, dalam domain dan disiplin filsafat, sains dan ilmu pengetahuan, demikian Thomas Nagel dalam bukunya yang berjudul The View from Nowhere, ada sebuah pertanyaan yang sangat urgen dan mendasar, yaitu bagaimana mengkombinasikan perspektif personal yang sifatnya partikular dalam sebuah dunia dengan pandangan objektif di dunia yang sama. Dan memang, masalah tersebut senantiasa hadir dalam kancah sains, filsafat dan ilmu pengetahuan, karena berkenaan dengan manusia sebagai subjek yang “mencari tahu” itu sendiri dan “apa yang ingin diketahui”. Belum lagi soal-soal lain yang berkenaan dengan itu semua. Menurut Muthahhari, suburnya paham dan gerakan materialisme di Barat tak dapat dilepaskan dari “kekurangan” doktrin Gereja Kristen dan kuatnya paham antropomorfisme Tuhan dalam doktrin Kristen dan Gereja Barat. Kita pun maphum, bahwa dalam sejarahnya, agama Kristen telah tercampur dengan paham dan budaya pagan Yunani-Romawi (Greco-Roman) ketika diterima di Eropa (Barat). Singkatnya, Kristen yang berasal dari Timur telah mengalami Westernisasi ketika hadir di Eropa.